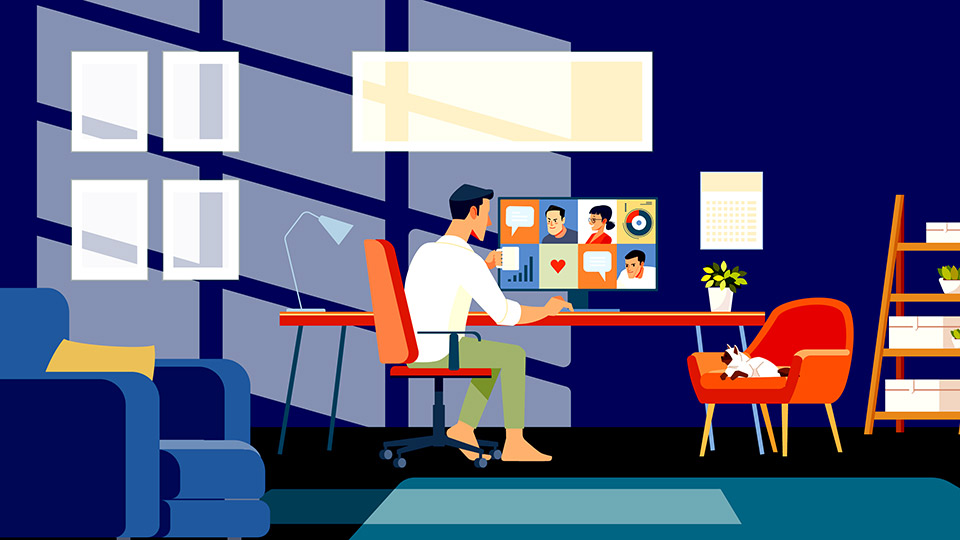Bayangkan karyawan yang baru direkrut, seorang diri masuk ke dalam organisasi yang tidak kelihatan wujudnya. Ia langsung berkantor di komputernya, tidak bisa mencium atmosfer kantor, hubungan dengan teman sekantor pun sebatas penyelesaian tugas. Jangankan karyawan baru, setelah sekian lama bekerja secara remote, karyawan lama pun bisa-bisa luntur perasaan belongingness-nya.
Padahal, Abraham Maslow, bapak motivasi kita, menekankan betapa pentingnya sense of belonging sebagai salah satu aspek yang sangat berpengaruh pada motivasi yang ujungnya akan berdampak pula pada produktivitas kerja. Sementara itu, saat ini kita sangat tergantung pada video call dan aktivitas layar komputer untuk tetap terhubung satu sama lain. Artinya, para profesional sumber daya manusia (SDM) dan jajaran manajemen perusahaan membutuhkan keterampilan khusus untuk mengelola sense of belongingness atau sense of community anak buahnya.
Riset membuktikan, perusahaan yang memiliki sense of belongingness yang tinggi ternyata dapat meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi brand mereka. Sebanyak 56 persen karyawan pun setuju, sense of belongingness dapat meningkatkan kinerja.
Dari segi neuroscience, sense of belongingness memang berpengaruh pada kesehatan mental individu secara keseluruhan. Sebuah rapat yang memiliki suasana menyenangkan akan merangsang hormon oxytocin peserta yang hadir. Oxytocin ini sering disebut sebagai feel good hormone yang akan merangsang attachment, mengintensifkan hubungan interpersonal, meredakan stres, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengkristalisasi memori-memori emosional. Oleh karena itu, penting bagi individu yang bekerja memiliki rasa senang dalam kehidupan sosialnya karena ini akan berkontribusi positif pada kinerja mereka.
Mengembangkan budaya belonging di tempat kerja hybrid
Menurut Viktor Frankl, manusia senantiasa berusaha mencari makna hidupnya yang dapat membuat hidup terasa berarti. Ada tiga jalan yang dapat dilalui oleh manusia untuk menemukan makna hidupnya, melalui pekerjaan, cinta, dan penderitaan. Mereka yang dapat menemukan makna melalui pekerjaannya tentu tidak akan segan untuk mengerahkan energinya dan berbuat lebih dari yang diharapkan.
Inilah sebabnya, setiap pemimpin perlu memikirkan bagaimana merancang kebijakan dan mengembangkan budaya yang membuat para karyawan apalagi pekerja generasi C (Covid) ini dapat memiliki kesempatan untuk menemukan makna dalam pekerjaannya, bukan sekadar kerja demi mendapatkan gaji pada akhir bulan.
Budaya perusahaan bukan menghilang atau berhenti berevolusi dalam situasi bekerja hybrid ini. Namun, memang dibutuhkan usaha yang lebih besar untuk mewujudkannya mengingat kita tidak berada dalam ruang yang sama. Meskipun kesempatan untuk memberi pengalaman kultural kepada para karyawan lebih terbatas, kita perlu percaya bahwa kultur tidak dibatasi empat dinding kantor saja. Kita dapat berfokus pada kebutuhan dasar individu yaitu kesehatan, produktivitas, kreativitas, dan sosial.
Ada beberapa tantangan yang perlu dicapai bila ingin memperdalam sense of belongingness karyawan di masa WFH ini. Pertama, menanamkan kultur belonging tanpa ketegangan. Pada dasarnya, individu yang bekerja juga memiliki kebutuhan sosial. Namun, bila kebutuhan sosial ini kemudian menjadi penuh tuntutan, hal yang dirasakan para karyawan adalah keterpaksaan. Penanaman kultur harus dilakukan dalam suasana menyenangkan yang merangsang hormon oxytocin.
Kedua, meretensi elemen sosial dari pekerjaan. Kerja bukan hanya bertujuan pada produktivitas. Kerja juga merupakan salah satu alat yang cukup berarti untuk berhubungan satu sama lain, yang bisa jadi merupakan pengalaman yang berharga sepanjang hidupnya. Melalui pekerjaan, kita bertumbuh dengan bimbingan para mentor, baik secara formal maupun informal. Rekan-rekan di kantor tempat kita menghabiskan lebih dari sepertiga waktu bersama, bergadang bersama, bisa berkembang menjadi sahabat seumur hidup karena bersama merekalah kita mengalami jatuh bangun dan berkembang bersama. Ini bisa menjadi alasan kita rindu pada suasana kantor kembali.
Gianpiero Petriglieri dari Insead menekankan, keinginan untuk kembali ke kantor itu adalah gabungan antara social pressure dan social excitement. Ternyata bertemu dengan kolega, sekaligus mengikuti aturan-aturan di kantor yang sebenarnya terkadang merupakan penekanan juga membawa rasa yang nyaman. Di sinilah tantangannya bagaimana kita dapat memberikan rasa terhubung, bahkan membangun kemesraan sambil juga memberikan peran pada para karyawan untuk menjadi bagian penting dari evolusi kultur yang sedang terjadi.
Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membentuk kebiasaannya sendiri. Sevirtual dan sedigital apa pun, kita tetap manusia yang menikmati hubungan dengan orang lain. People are longing for the connective tissue and social glue we once took for granted. Situasi inilah yang perlu kita akomodasi.
Ketiga, percaya bahwa kultur perusahaan akan berevolusi. Di setiap organisasi, kultur perusahaan sangat dipengaruhi legacy. Ada sejarah perusahaan dengan pemimpin-pemimpin masa lalu yang gaungnya masih terasa di situasi sekarang. Godaan kita untuk berpegang pada masa lalu itu sangat kuat. Namun, dengan adanya disrupsi dan perubahan di tempat kerja, kultur perusahaan pasti berevolusi.
Kita memang belum tahu bentuk masa depan kehidupan kantor hybrid ini. Namun, kita perlu meyakini, sistem ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin kantor yang lebih menekankan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi dapat menjadi katalis untuk merangsang pertemuan one on one, atau pertemuan di luar kantor untuk sekadar bersenang-senang. Kantor dibuat tidak sekadar tempat kerja, tetapi juga sebagai pusat komunitas, melakukan internal networking. Pada saat inilah akan terasa bahwa budaya perusahaan dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih sosial dan personal.
Eileen Rachman & Emilia Jakob
HR Consultant/Konsultan SDM