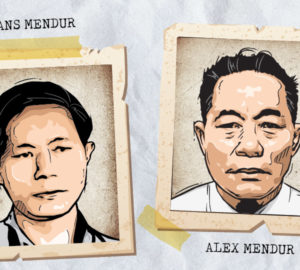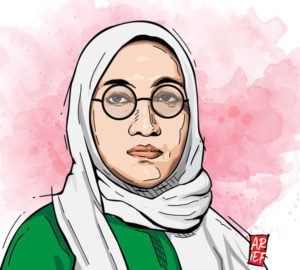Sungai Saddang dekat Bukit Singki menjadi saksi bisu gugurnya Pong Tiku, pahlawan nasional asal Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Nama Pong Tiku barangkali terdengar asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak banyak pula yang tahu bahwa pada 8 November 2002 Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Pong Tiku. Namun, tidak demikian halnya dengan masyarakat Toraja, yang sejak lama memperjuangkan gelar tersebut. Bagi mereka, Pong Tiku memang pahlawan dan simbol perjuangan terhadap kolonial Belanda.
Pong Tiku alias Ne Baso lahir di Pangala’, kawasan dataran tinggi Sulawesi yang sekarang termasuk Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 1846. Ia anak dari penguasa Pangala’, Siambo’ Karaeng dan istrinya, Leb’ok. Kala itu, Sulawesi Selatan sedang mengalami booming perdagangan kopi. Perdagangan dikontrol oleh para penguasa lokal, termasuk Siambo’ Karaeng.
Setelah ayahnya wafat, Pong Tiku naik menggantikan sebagai penguasa Pangala’. Ia memperkuat perekonomian setempat melalui perdagangan kopi dan menjalin hubungan dengan suku-suku Bugis di dataran rendah. Ketegangan yang terjadi di antara negara-negara di utara dan selatan Pangala’ memicu meletusnya Perang Kopi pada 1889 hingga 1890. Ibu Kota Tondon sempat dikuasai lawan sebelum direbut kembali oleh Tiku. Setelah itu, ia memperkuat pertahanan dengan membangun sejumlah benteng.
Awal abad ke-20, Belanda mulai menyerang Sulawesi Selatan. Para penguasa lokal berhenti berperang satu sama lain dan memusatkan perhatian pada Belanda yang memiliki kemampuan jauh lebih unggul. Namun, satu per satu kerajaan di Sulawesi Selatan runtuh dan ditaklukkan Belanda, hingga menyisakan Tiku sebagai penguasa terakhir Toraja.
Pada 1906, Belanda sudah menguasai hingga sejauh Rantepao. Utusan dikirim ke Tondon, tetapi Tiku menolak untuk menyerah. Ia malah menyerang pasukan Belanda. Namun, dengan persenjataan lebih lengkap, Belanda mampu menaklukkan benteng Tiku di Lali’Londong. Menjelang akhir tahun, dua benteng lain akhirnya berhasil ditaklukkan Belanda, setelah gagal berulang kali.

Sepak terjang Tiku membuat Gubernur Jenderal Belanda JB Van Heutsz memerintahkan Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin langsung penyerangan pada pasukan Tiku. Pasalnya, peperangan melawan Tiku memakan waktu lebih lama dibandingkan pendudukan tempat-tempat lain. Hal itu dianggap mencoreng muka Van Heutsz.
Setelah pengepungan sekian lama dan negosiasi dengan mantan anak buahnya yang kemudian bekerja untuk Belanda, Tiku setuju untuk gencatan senjata. Awalnya ia enggan, tetapi karena diingatkan bahwa ibunya yang gugur dalam pengepungan harus dimakamkan, ia pun setuju dan dipaksa pergi ke Tondon.
Mencium gelagat bahwa ia akan ditangkap, malam sebelum pemakaman ibunya pada Januari 1907, Tiku melarikan diri bersama 300 pengikutnya ke arah selatan. Meski harus terus mundur menyusul jatuhnya bentengnya satu per satu, Tiku tidak mau menyerah pada Belanda.
Persembunyian Tiku di hutan mulai terlacak Belanda dan pada 30 Juni 1907, ia dan dua pasukannya ditangkap oleh pasukan Belanda. Tiku menjadi pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Setelah beberapa hari ditahan, pada 10 Juli 1907 Tiku gugur ditembak pasukan Belanda di Sungai Saddang. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga di Tondol.
Meski telah tiada, semangat Tiku justru menjadi inspirasi dan simbol perjuangan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi. Untuk menghormati jasa-jasanya, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengangkat Tiku sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Pada 1970, tugu penghormatan Tiku didirikan di tepi Sungai Sa’dan. Namanya juga dijadikan nama bandara di Tana Toraja. Dan, akhirnya, pada 2002 pemerintah RI mengakui Tiku sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.